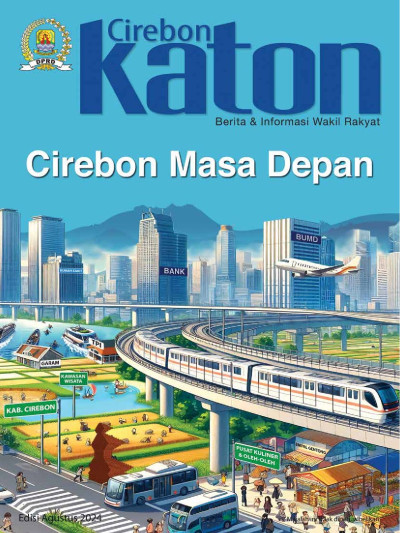Menilik Tingginya Angka Putus Sekolah
Baru juga subuh berkumandang, Karyadi sudah terjaga. Memanaskan Astuti. Motor bututnya yang biasa ia gunakan pergi meladang. Ketika teman sebayanya bersiap mandi dan memakai seragam sekolah, Karyadi justru menyiapkan cangkul dan sprayer. Seperti biasa, selepas salat subuh, Karyadi akan berangkat ke sawah milik bosnya.
“Saya kerja di sawah orang. Jadi jam 6 saya harus sudah di tempat. Dulu saya cuma sekolah SD, itu juga hanya sampai kelas 5. Saya berhenti karena merasa enggak nyaman ibu sama bapak saya hanya buruh tani tapi mereka harus membiayai sekolah saya dan kakak saya yang waktu itu sudah SMP,” ujar Karyadi.
Semenjak tidak sekolah, Karyadi pun diminta membantu ibu dan bapaknya bekerja di sawah. Di usia 16 tahun kala itu, Karyadi bahkan sempat merantau bekerja bersama saudaranya ke Sulawesi.
“Umur 14 tahun saya sudah ikut ke sawah sama bapak. Dulu bayarannya Rp 35 ribu sekarang sudah Rp 60 ribu. Terus saya juga pernah ke Sulawesi, di sana saya kerja proyek pembangunan,” ujarnya.
Karyadi pun harus memaksakan tubuhnya untuk bekerja laiknya orang dewasa. Karyadi memang tak punya pilihan.
“Umur saya sekarang 19 tahun, saya juga pengen bisa lanjut sekolah, tapi malu kalau harus ngulang dari SD. Belum lagi biaya pendaftaran atau buat kebutuhan lainnya, saya bingung buat bagi-bagi keperluannya. Apalagi sayas juga harus bisa ngasih ke orangtua,” ucap Karyadi.
Saat ini Karyadi pun memilih bekerja di sekitar tempat tinggalnya. Dari menggarap sawah hingga kuli proyek bangunan. Ia tak ingin merantau jauh kembali. “Saya cuman pengen dekat dengan kedua orangtua saja kalau sekarang,” tuturnya.
Tak jauh berbeda dengan Sarda’i (20), pemuda Desa Sindangmekar. Ia hanya menamatkan sekolah dasar. Tahun 2012 setelah ia lulus, Sarda’i diminta bekerja oleh ibunya. Ibunya tak bisa lagi bekerja setelah sakit kaki yang didera. Ia pun terpaksa harus membantu menafkahi keluarga.
“Bapak sudah enggak ada juga. Makanya saya diminta bantu ibu. Saya kerja di pasar Tegalgubug ikut paman saya. Sekarang saya kerja di pemolaan pembuatan kusen,” ujar Sarda’i.
Sarda’i berkeinginan melanjutkan pendidikanya. Untungnya saat ini ia mendapat kemudahan dengan dibantu lembaga masyarakat melanjutkan ke jenjang kejar paket.
Sementara Sandi, pemuda asal Desa Rawaurip mungkin lebih beruntung. Ia sempat melanjutkan ke SMP Ma’arif Pangenan meski harus berhenti setelah dua semester berjalan.
“Dulu saya bingung, karena saat itu orang tua sakit-sakitan dan saya juga merasa tidak nyaman di sekolah. Jadi sampai semester 2 saya sudah jarang berangkat, terkadang saya bantuin orangtua saya bekerja di sawah,” kata Sandi.
Selepas putus sekolah, Sandi juga sempat merantau ke Bekasi dan Bogor. Bermodal dengan ijazah SD, Sandi tidak berharap lebih untuk dapat kerja. Ia sempat jualan minuman keliling untuk menghidupi.
“Saya pernah merantau di Bekasi dan Bogor selama 5 tahun. Di sana saya kerja apa aja, kadang jualan minuman bersama saudara. Sekarang saya kerja serabutan, terkadang buruh tani, buruh lepas di pabrik, dan ikut jadi panjak burok di daerah saya,” paparnya.
Sandi sempat berkeinginan mengikuti sekolah penyetaraan SMP, tapi ia tak punya biaya. Ia hanya tahu, tak ada sekolah yang gratis meski itu kejar paket. Penghasilannya yang belum menentu saat itu, menjadi penyebab ia mengurungkan niatnya.
“Pernah sih ditawari sama temen buat kejar paket B, tapi belum apa-apa sudah pusing mikirin biayanya dari mana. Saya enggak enak kalau harus minta ke orangtua, mereka juga lagi susah belum lagi ibu yang sedang sakit,” katanya menghela nafas.
Meski demikian, Kasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon Muhammad Rukhyat mengaku, Disdik terus berupaya mengurangi jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Cirebon.
“Sampai saat ini jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Cirebon semakin berkurang. Di tingkat SMP yang pada 2019 berjumlah 215, di tahun 2021 sudah turun menjadi 84. Sementara yang tingkat SD pada tahun 2019 berjumlah 62, di tahun 2021 menjadi 16 anak,” ungkap Rukhyat.
Rukhyat pun menilai, faktor penyebab masih ada anak putus sekolah karena suasana sekolah tak nyaman maupun sistem Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang membosankan. Selain itu, masih kurangnya kepedulian dari keluarga dalam mengatur pendidikan anak.
“Terkadang ada orangtua ingin anaknya sekolah di SMP terbaik, tapi kemampuan anaknya tidak mampu jadi malah enggak nyaman. Sering juga terjadi orangtua yang kurang mendorong anak sekolah karena orangtua sibuk kerja dan sebagainya,” jelas Rukhyat.
Oleh karena itu ia berharap, orangtua juga harus bisa mengedukasi anaknya agar bersemangat untuk sekolah dan bukan hanya mau. Menurutnya, setiap anak berhak mendapat pendidikan selama 12 tahun.
Ketua PGRI Kabupaten Cirebon Yeyet Nurhayati juga berpendapat, faktor utama angka putus sekolah yang umumnya karena keluarga. Baik karena broken home, ada juga orangtua yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Akibatnya anak tidak terkontrol. Faktor lainnya karena kualitas SDM orangtua siswa yang rendah.
“Jadi banyak yang mencukupkan anaknya hanya tamat sekolah SD atau orangtua hanya mencukupkan anaknya hanya bisa baca dan tulis saja. Jadi boro-boro untuk lanjutkan SMP,” ujar Yeyet
Selain itu, ekonomi juga menjadi penyebab. Terutama di pelosok kampung. Orangtua yang berpikiran kolot beranggapan sekolah itu hanya membuang biaya. Mau tidak-mau, kata Yayat, mereka hanya ingin menyekolahkan anak di sekolah negeri karena murah. Sementara ketika anak tak diterima di negeri, mereka enggan menyekolahkannya ke swasta karena biayanya yang mahal.
“Sehingga anak pun dicukupkan untuk sekolah. Orangtua juga enggak ngerasa bersalah. Karena di sisi lain beban ekonomi keluarga jadi berkurang,” tuturnya.
Sementara saat ini, akibat pandemi banyak juga anak yang berhenti sekolah karena pembelajaran yang mengharuskan daring. Namun persoalannya tidak semua orangtua mampu memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring baik gawai maupun jaringan internet. Sehingga sebagian orangtua pasrah dan memutuskan anak berhenti sekolah.
Di luar dari persoalan internal, lanjut Yeyet, faktor lain seorang siswa berhenti melanjutkan pendidikan juga karena tak diterima di sekolah tertentu yang menjadi dambaan. Maka tidak aneh, kalau sebagian sekolah yang justru mendapatkan murid sedikit, sementara lainnya kekurangan kelas rombongan belajar (rombel).
“Itu karena tidak ada ketegasan untuk mengatur kuota siswa tiap sekolah. Jadi yang sudah penuh justru nambah rombel. Sekolah lain rombelnya ada, siswanya yang kurang,” kata Yeyet.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Nana Kencanawati juga menilai peran orangtua yang memiliki pengaruh penting dalam melakukan langkah preventif anak putus sekolah.
“Pergaulan anak-anak desa sekarang ini saja sudah berubah karena teknologi semakin cepat. Cara berpikir anak instan. Mereka mudah terbawa arus percepatan teknologi tanpa mencerna dan mencari jati diri. Karena kecanduan bermain gawai sehingga malas untuk bersekolah itu juga jadi penyebab,” kata Nana.
Sehingga menurutnya, peran kolaborasi dalam memberikan edukasi orangtua menjadi penting. Agar mendorong anaknya tetap sekolah. Sementara bagi mereka yang mengalami keterbatasan ekonomi, kata Nana, bisa diselesaikan melalui bantuan sosial yang bisa dimanfaatkan untuk bidang pendidikan.
“Bantuan dari pemerintah desa jangan hanya dialokasikan untuk bantuan sosial. Tetapi juga untuk bantuan pendidikan. Memang sekarang susah karena bantuan sosial harus diutamakan untuk pandemi. Tetapi kalau pandemi selesai alokasi bantuan juga harus disisihkan untuk pendidikan anak yang tak mampu di desa,” pungkasnya. *Par